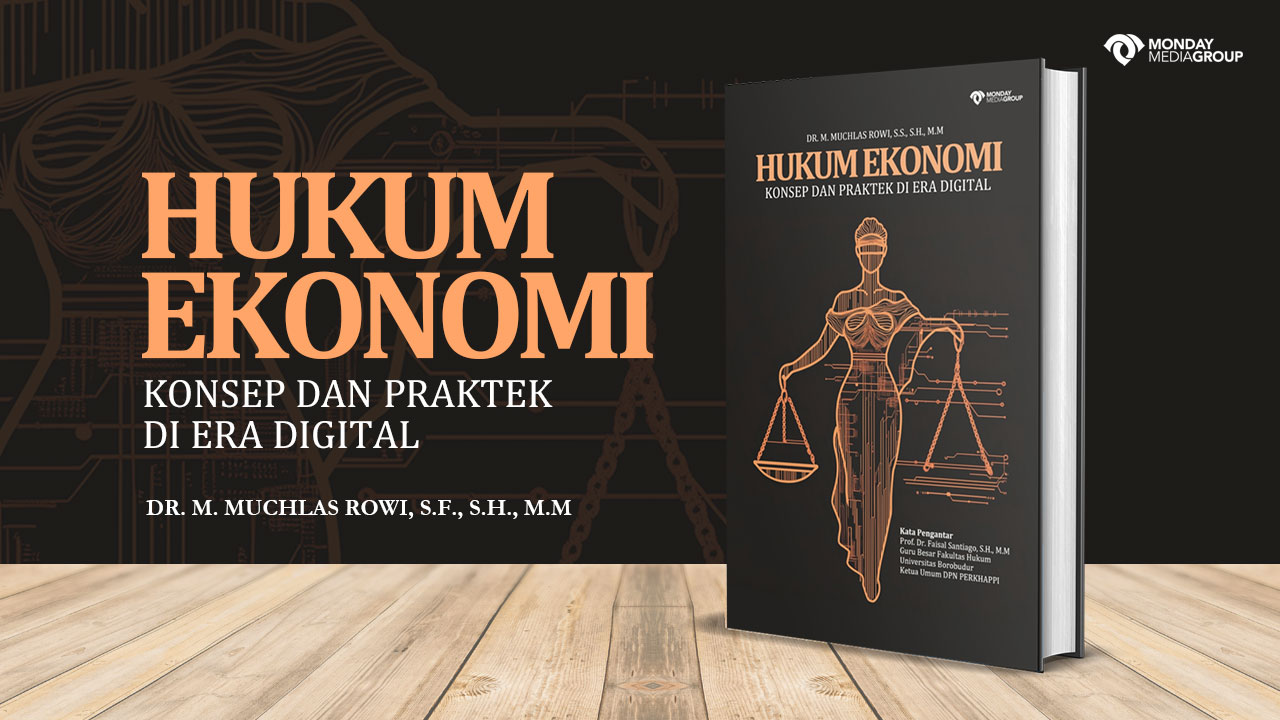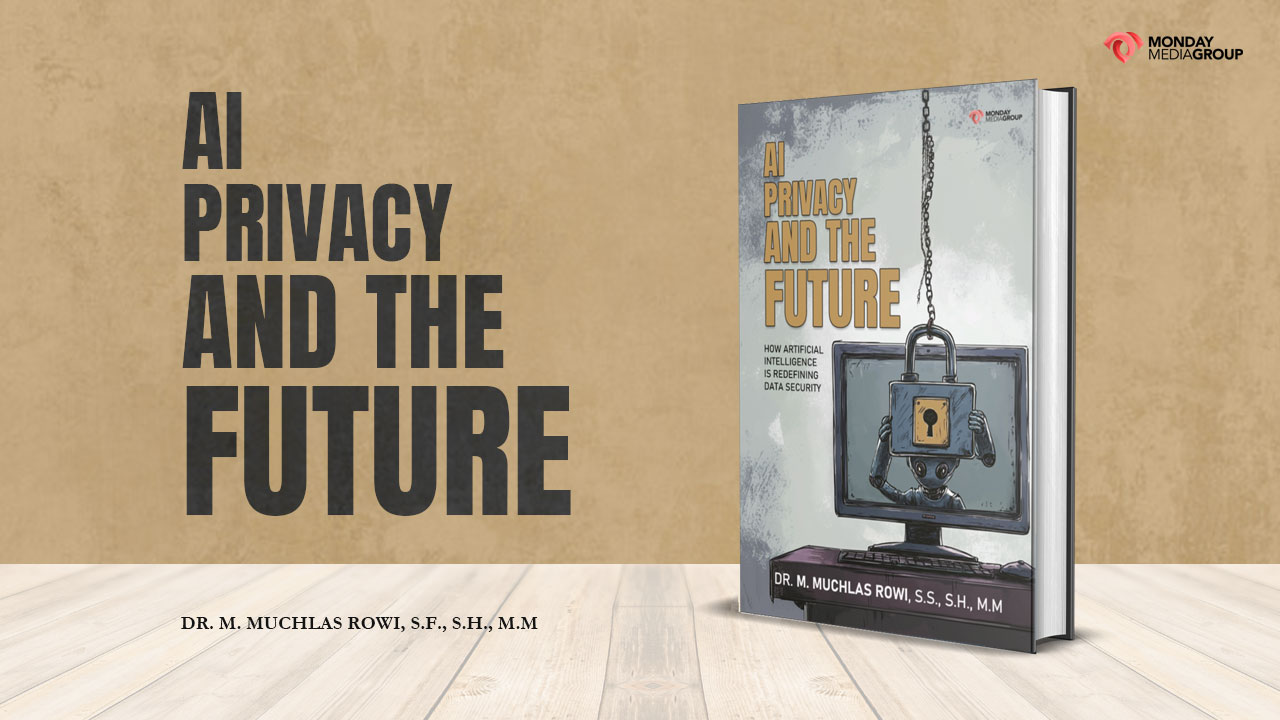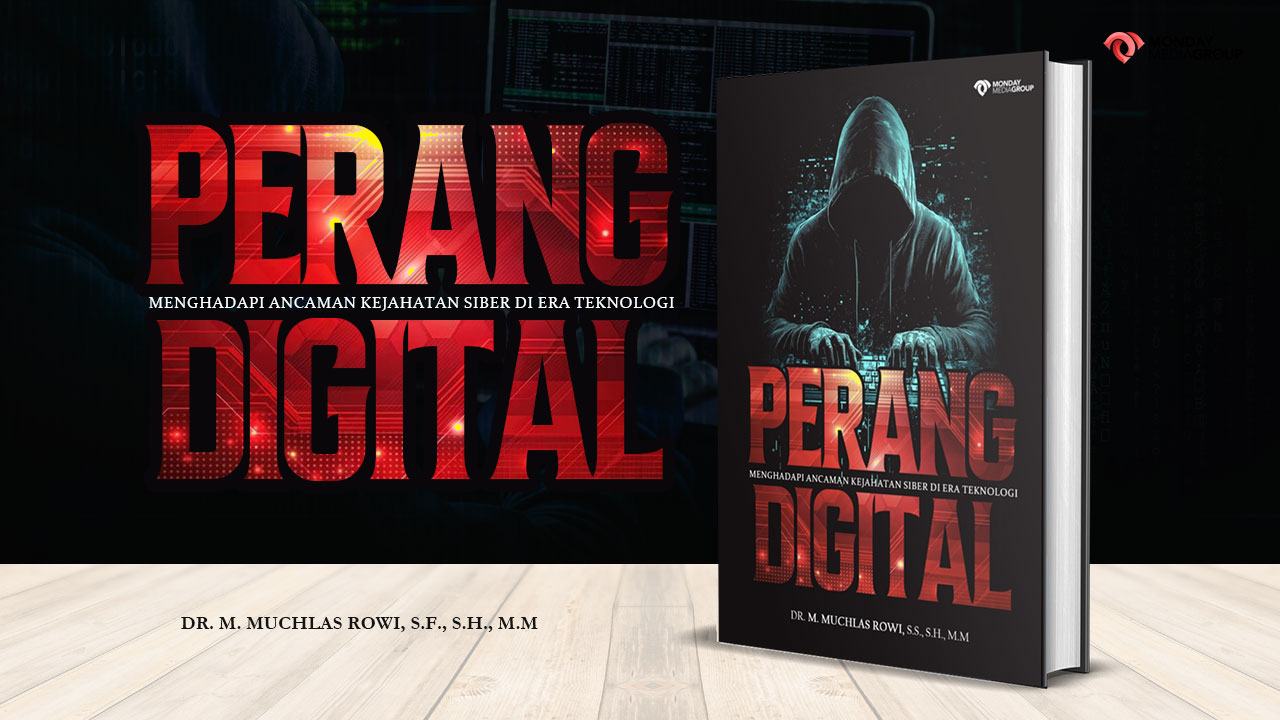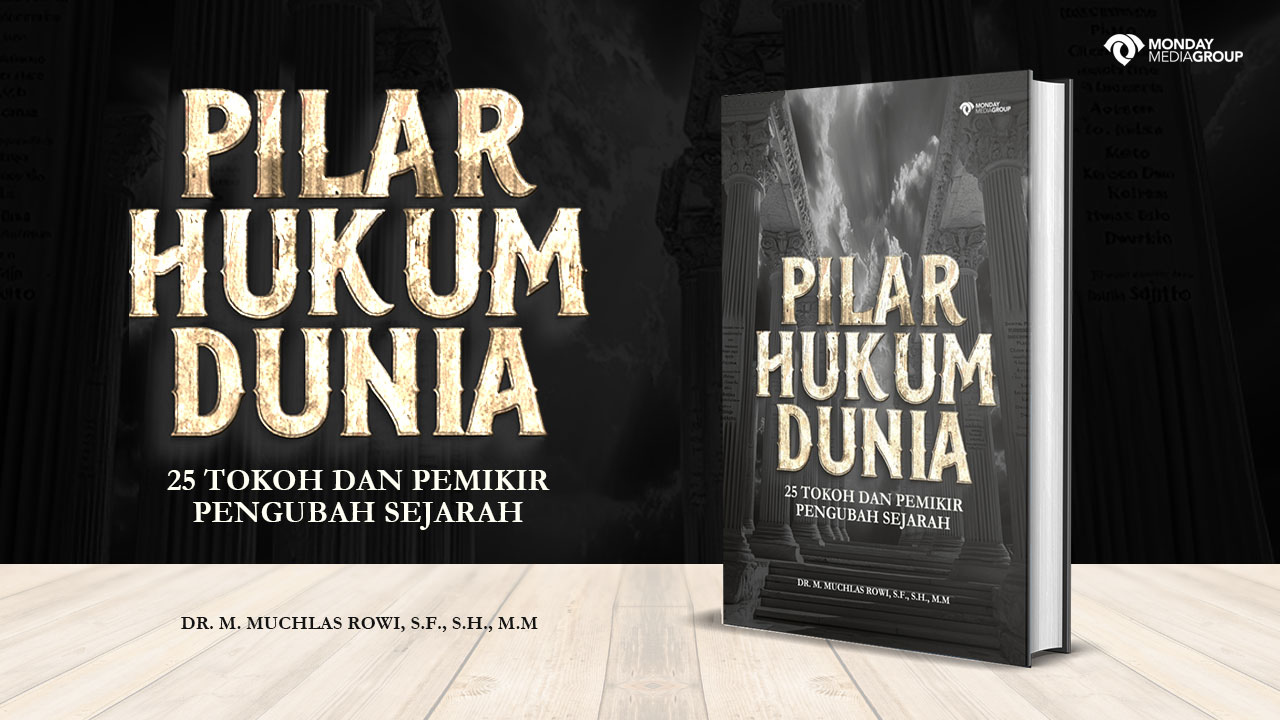Menulis buku Hukum Ekonomi: Konsep dan Praktek di Era Digital bukanlah perkara mudah, bukan pula sekadar menumpahkan teori ke atas kertas. Saya merasa perlu menuliskannya karena satu hal yang terus mengganggu benak saya selama bertahun-tahun: kenapa kita selalu membicarakan hukum dan ekonomi seolah-olah keduanya berdiri di ruang yang berbeda?
Padahal, dalam kehidupan nyata, keduanya saling bertaut. Bahkan, saya percaya bahwa hukum dan ekonomi adalah dua sisi dari koin yang sama. Yang satu mengatur, yang lain bergerak. Yang satu memberi batas, yang lain mendorong. Dan dalam konteks Indonesia hari ini, keduanya harus berdialog lebih dalam dari sebelumnya.
Saya membuka buku ini dengan membahas akar sejarah hukum ekonomi. Dari Codex Hammurabi di Babilonia sampai prinsip-prinsip ekonomi Rasulullah di Madinah. Dari hukum Solon di Yunani hingga regulasi dagang di masa Umar bin Khattab. Sejak zaman dahulu, manusia sudah tahu bahwa aktivitas ekonomi yang liar tanpa hukum akan berujung pada ketimpangan dan kekacauan.
Di Indonesia sendiri, saya melihat tantangan hukum ekonomi tidak hanya datang dari lemahnya penegakan hukum, tapi juga dari jurang antara norma konstitusi dan praktik kebijakan. Terlalu banyak kebijakan ekonomi kita yang dibuat reaktif, pragmatis, dan melupakan roh konstitusi. Kita punya cita-cita ekonomi kerakyatan yang luhur, tapi implementasinya kadang condong ke logika pasar bebas murni.
Dalam buku ini, saya mencoba membedah itu semua. Saya menempatkan konstitusi sebagai fondasi dari seluruh kebijakan ekonomi. Kita tidak bisa terus-menerus menyusun strategi pembangunan tanpa berpijak pada prinsip keadilan sosial, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Banyak orang mengira hukum ekonomi hanya urusan pajak, perizinan, dan kontrak. Padahal, hukum ekonomi juga berbicara tentang siapa yang boleh mendapatkan manfaat dari pembangunan. Siapa yang diberi akses terhadap lahan, siapa yang dilindungi dari gejolak pasar, dan siapa yang harus didahulukan saat krisis melanda.
Salah satu hal yang saya soroti adalah ketimpangan dalam pendekatan pembangunan. Kita terlalu fokus pada pertumbuhan, namun lupa pada distribusi. Maka saya bagi kerangka hukum ekonomi dalam dua sayap besar: Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial. Yang pertama bicara soal pertumbuhan, efisiensi, investasi. Yang kedua bicara soal pemerataan, perlindungan sosial, dan keadilan struktural.
Buku ini juga saya lengkapi dengan banyak studi kasus—dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai contoh hukum ekonomi sosial, hingga krisis 1997-1998 yang mengajarkan betapa pentingnya regulasi keuangan yang kuat. Saya angkat pula tokoh-tokoh besar, dari Adam Smith hingga Amartya Sen, dari Karl Marx hingga Joseph Stiglitz, untuk memberi dimensi filosofis pada perdebatan hukum dan ekonomi yang kadang terlalu teknokratis.
Namun yang membuat buku ini menjadi relevan saat ini adalah bab-bab akhir yang membahas era digital. Kita tidak bisa bicara ekonomi hari ini tanpa menyentuh e-commerce, data pribadi, fintech, kripto, dan kecerdasan buatan. Di sinilah hukum diuji untuk benar-benar lincah. Di sinilah negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak ketinggalan zaman.
Saya menulis, “Regulasi digital tidak bisa dibuat di ruang hampa.” Sebab kini, keputusan perusahaan raksasa digital bisa berdampak pada UMKM di pelosok. Algoritma bisa menentukan siapa yang melihat produk siapa. Data bisa diperdagangkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dunia digital membutuhkan hukum yang tidak hanya reaktif, tapi juga visioner.
Maka, saya mengajak pembaca—baik dari kalangan hukum, ekonomi, birokrasi, maupun masyarakat luas—untuk mulai memikirkan ulang hubungan antara hukum dan ekonomi di negeri ini. Bukan untuk menyusun ulang teori, tapi untuk membumikan prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati sejak lama: keadilan sosial, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan.
Saya menulis buku ini tidak untuk menggurui. Tapi untuk mengajak berdiskusi. Karena saya percaya, pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya diserahkan pada pasar. Ia butuh arah. Dan arah itu, hanya bisa ditentukan oleh hukum.
Mari kita rawat harapan itu—dengan data, dengan nurani, dan tentu saja, dengan kerja keras.