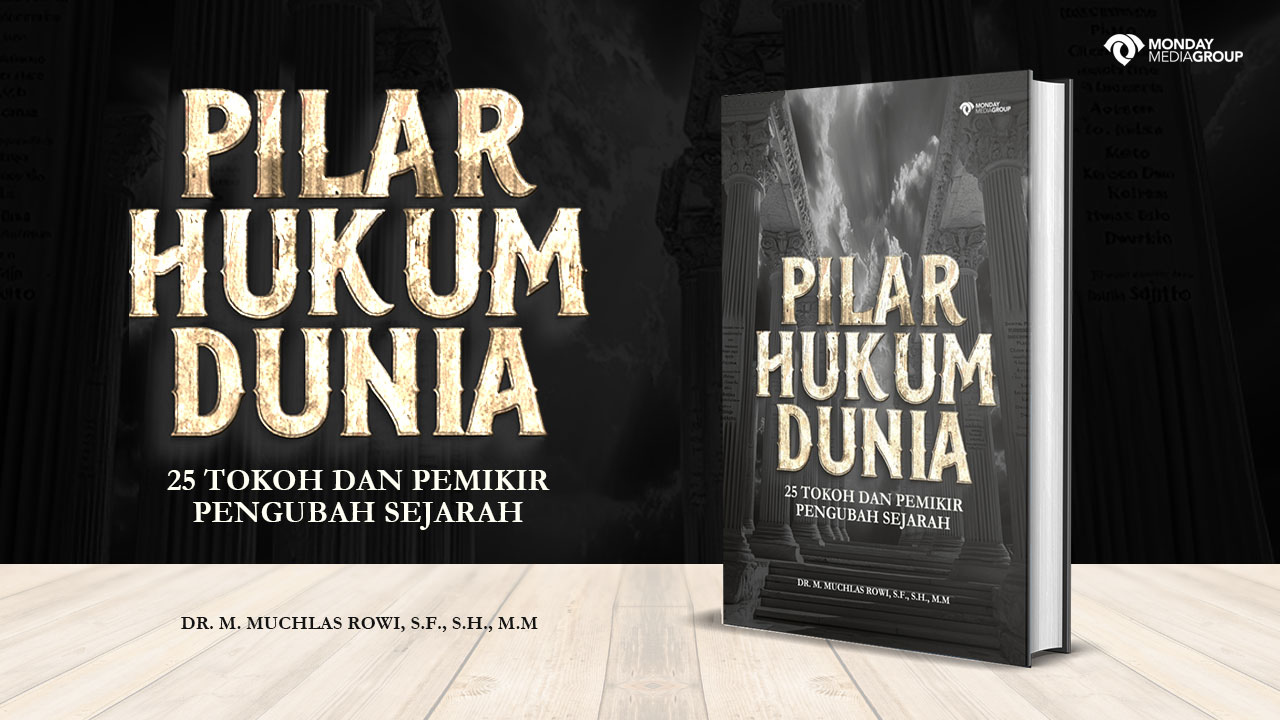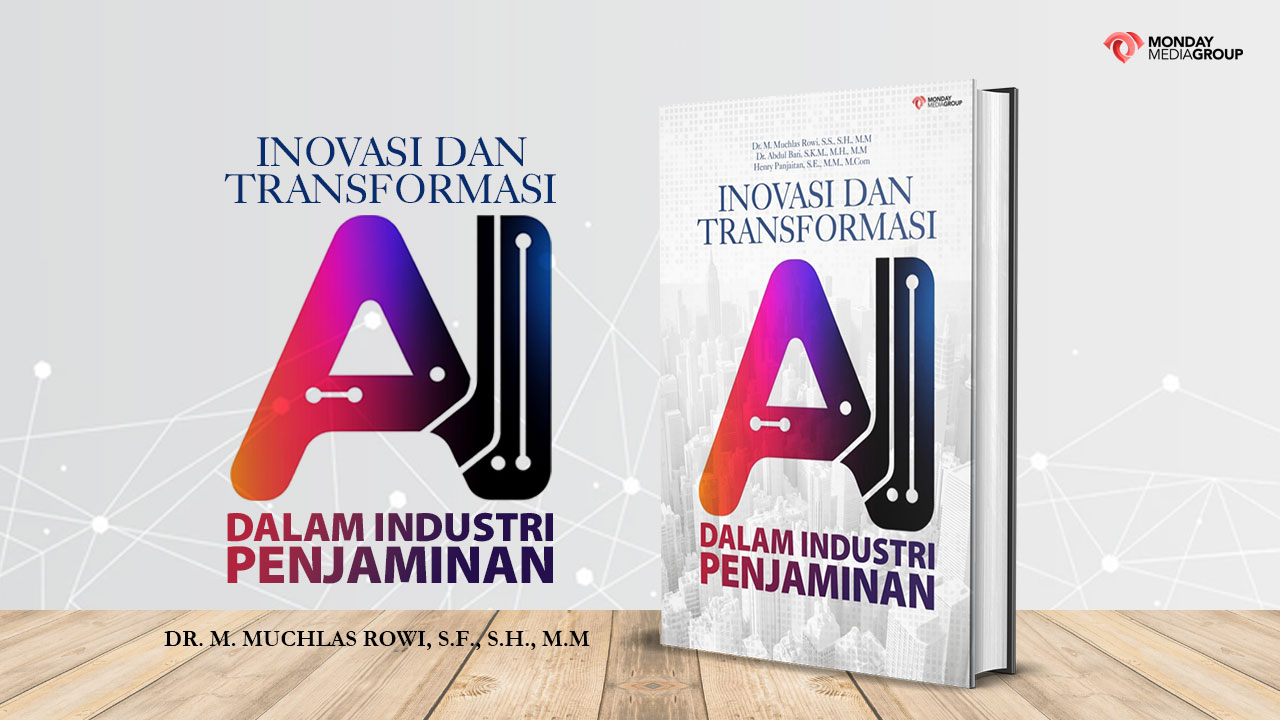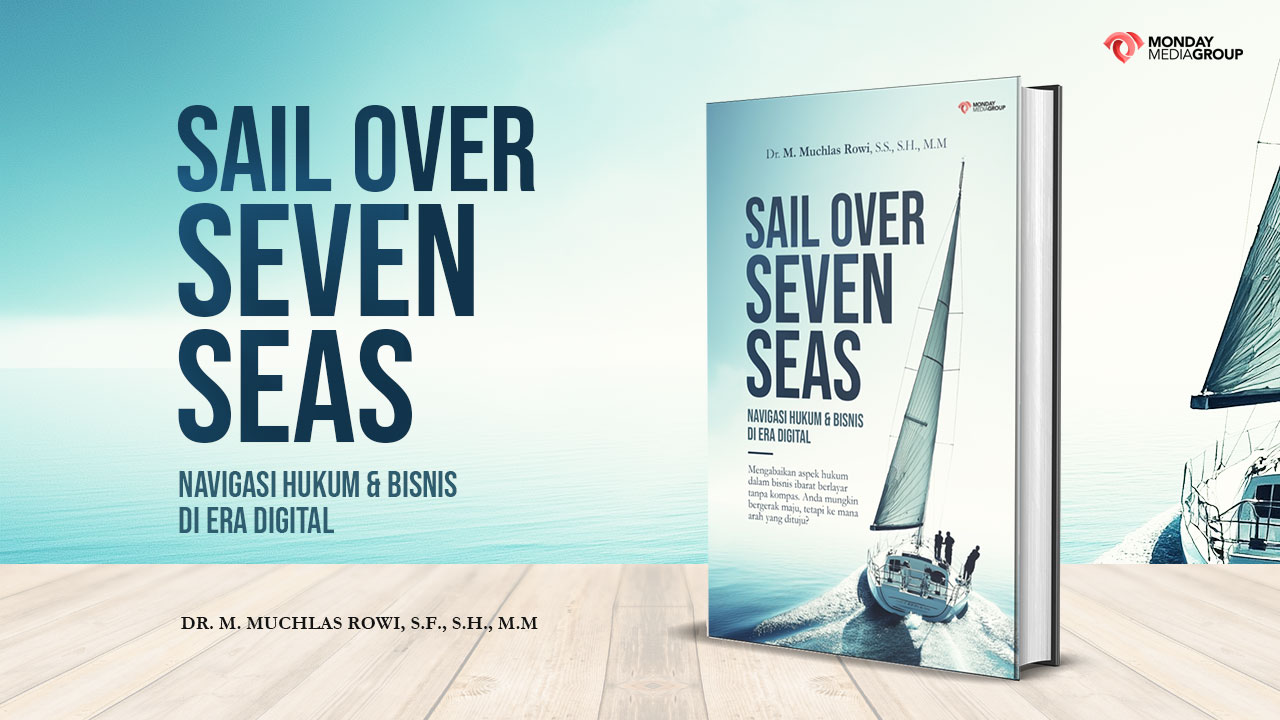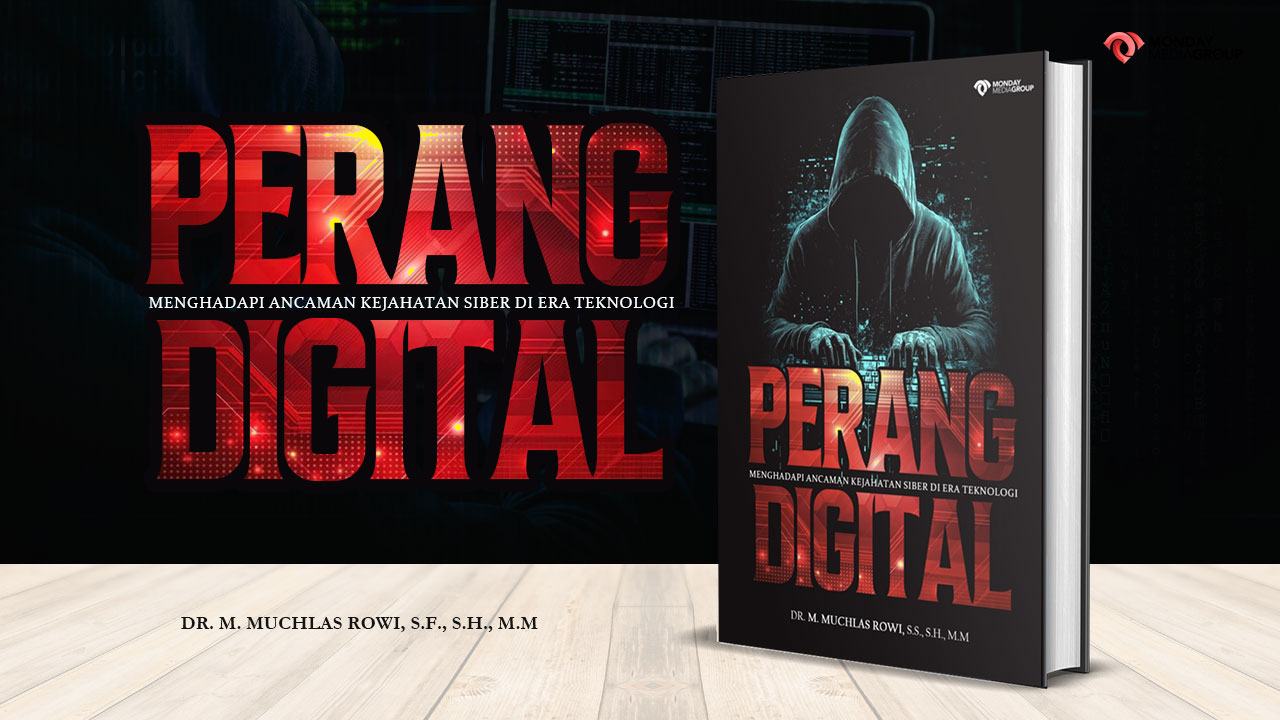Ketika saya memulai penulisan buku Pilar Hukum Dunia, saya tidak hanya sedang menyusun kembali jejak-jejak pemikiran hukum dari ribuan tahun yang lalu hingga hari ini, tetapi juga sedang mengajak diri saya sendiri dan pembaca untuk menyusuri kembali hakikat paling dasar dari hukum: mengapa manusia membutuhkan hukum? Dari mana legitimasi sebuah aturan berasal? Dan, lebih dari itu, apa yang membuat hukum tidak hanya sah, tetapi juga adil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah menjadi renungan sejak zaman Socrates duduk di Agora Athena, mempertanyakan tentang kebenaran dan keadilan, hingga hari ini, saat kita menghadapi kompleksitas hukum di era digital, global, dan bahkan absurd. Dalam perjalanan itulah, saya mengajak pembaca untuk mengenal para pemikir hukum bukan sebagai figur akademis yang jauh dari kenyataan, tetapi sebagai penyalur harapan akan dunia yang lebih tertib dan adil.
Dari Socrates hingga Amartya Sen: Sebuah Dialog Lintas Zaman
Buku ini menghadirkan 25 tokoh pemikir hukum dari berbagai zaman dan tradisi, mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles, hingga Dworkin, Posner, dan Amartya Sen. Setiap tokoh bukan hanya saya bahas dari sisi teorinya, tetapi juga saya hubungkan dengan realitas sosial-politik zamannya.
Misalnya, dalam membahas Socrates, saya menyoroti bagaimana filsuf besar itu tidak hanya berpikir tentang keadilan secara abstrak, tetapi hidup dalam integritas terhadap prinsip hukumnya sendiri. “Ia menolak untuk melarikan diri dari penjara, dan menerima hukuman mati sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum,” tulis saya dalam bab Socrates. Pilihannya menunjukkan bahwa bagi Socrates, hukum bukan sekadar aturan eksternal, tetapi bagian dari moralitas dan kewajiban warga negara yang sadar.
Lalu dalam membahas John Locke, saya menekankan peran pemikirannya dalam membentuk ide tentang hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional. Locke menulis bahwa pemerintahan yang sah hanya dapat berdiri atas dasar “consent of the governed”—persetujuan yang diperintah. Konsep ini, dalam hemat saya, merupakan salah satu pilar konstitusionalisme modern yang tetap menjadi penyangga negara hukum di berbagai belahan dunia hingga hari ini.
Sementara itu, Amartya Sen, seorang pemikir kontemporer yang saya masukkan dalam daftar, menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup diukur melalui formalisme hukum semata. Dalam bukunya The Idea of Justice, Sen berargumen bahwa keadilan adalah soal memperluas kebebasan dan kapabilitas manusia. Saya menuliskan bahwa “pemikiran Sen mengajak kita untuk melihat hukum sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan, bukan sekadar struktur aturan.”
Mengapa Hukum Tak Pernah Netral
Selama proses penulisan, saya berusaha menghindari jebakan positivisme hukum yang kering. Seperti saya tulis dalam prolog buku: “Hukum tidak lahir dari kehampaan. Ia adalah produk dari pergulatan manusia melawan kekuasaan yang sewenang-wenang, ketimpangan sosial, dan kekacauan moral.”
Banyak dari para pemikir yang saya angkat dalam buku ini adalah mereka yang justru berani menggugat hukum, karena mereka percaya bahwa hukum harus berpihak kepada yang lemah, kepada nilai, dan kepada keadilan substantif. Marx, misalnya, secara tajam menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi alat dari kelas penguasa. Di sisi lain, Ronald Dworkin berargumen bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari prinsip moral. Dalam Law as Integrity, Dworkin menulis bahwa hakim harus menafsirkan hukum “dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan koherensi, bukan sekadar teks.”
Inilah mengapa saya percaya: Memahami sejarah pemikiran hukum adalah langkah awal untuk membentuk kesadaran hukum yang lebih adil dan manusiawi.
Mengapa Tokoh Indonesia Harus Hadir dalam Peta Dunia
Satu keputusan penting dalam penulisan buku ini adalah memasukkan tiga tokoh hukum Indonesia dalam barisan para pemikir dunia: Prof. Satjipto Rahardjo, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dan Prof. Bagir Manan. Mengapa?
Karena hukum bukan monopoli Barat. Kita memiliki pemikir hukum yang tidak hanya orisinal, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Satjipto Rahardjo, misalnya, menolak hukum yang kaku dan tidak berpihak. Ia menulis, “Hukum harus mengalir bersama kehidupan, bukan membekukannya.” Dalam bab tentang beliau, saya menulis bahwa hukum progresif adalah napas keadilan sosial yang dibutuhkan Indonesia hari ini.
Mochtar Kusumaatmadja, di sisi lain, membangun gagasan hukum pembangunan. Ia menjadikan hukum sebagai alat diplomasi internasional dan instrumen modernisasi nasional, termasuk dalam konteks hukum laut Indonesia melalui Wawasan Nusantara.
Sementara Bagir Manan, yang tenang dan mendalam, membangun teori konstitusi yang menyelaraskan demokrasi, hukum dasar, dan hak-hak rakyat. Pemikirannya menunjukkan bahwa konstitusi bukan sekadar teks legalistik, tapi harus menjadi sarana untuk menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga martabat rakyat.
Saya ingin pembaca Indonesia sadar: bahwa kita juga memiliki pemikir-pemikir besar yang harus terus dibaca, dikaji, dan diajarkan di ruang-ruang kelas hukum.
Hukum Sebagai Cermin Kehidupan
Buku ini tidak saya maksudkan sebagai katalog biografi, melainkan sebagai “perjalanan naratif yang mencoba mengaitkan pikiran dan konteks, ide dan zaman, filsafat dan kenyataan.” Saya ingin pembaca tidak hanya tahu siapa Locke, Grotius, Kelsen, atau Hart, tetapi juga mengapa pemikiran mereka tetap hidup hari ini.
Saya berharap buku ini bisa menjadi teman diskusi lintas zaman. Sebagaimana saya tulis di bagian akhir prolog: “Bacalah tokoh demi tokoh bukan hanya sebagai fakta sejarah, tetapi sebagai teman diskusi yang mengajak Anda merenungkan kembali dunia hukum hari ini.”
Di tengah dunia yang berubah cepat—dari kecerdasan buatan, disrupsi teknologi, hingga krisis iklim—kita membutuhkan hukum yang lebih dari sekadar teks. Kita butuh hukum yang punya jiwa, yang mampu berdialog dengan zaman, dan yang bisa melindungi nilai-nilai kemanusiaan.
Pilar Hukum Dunia bukan hanya tentang sejarah. Ia adalah refleksi tentang masa depan.