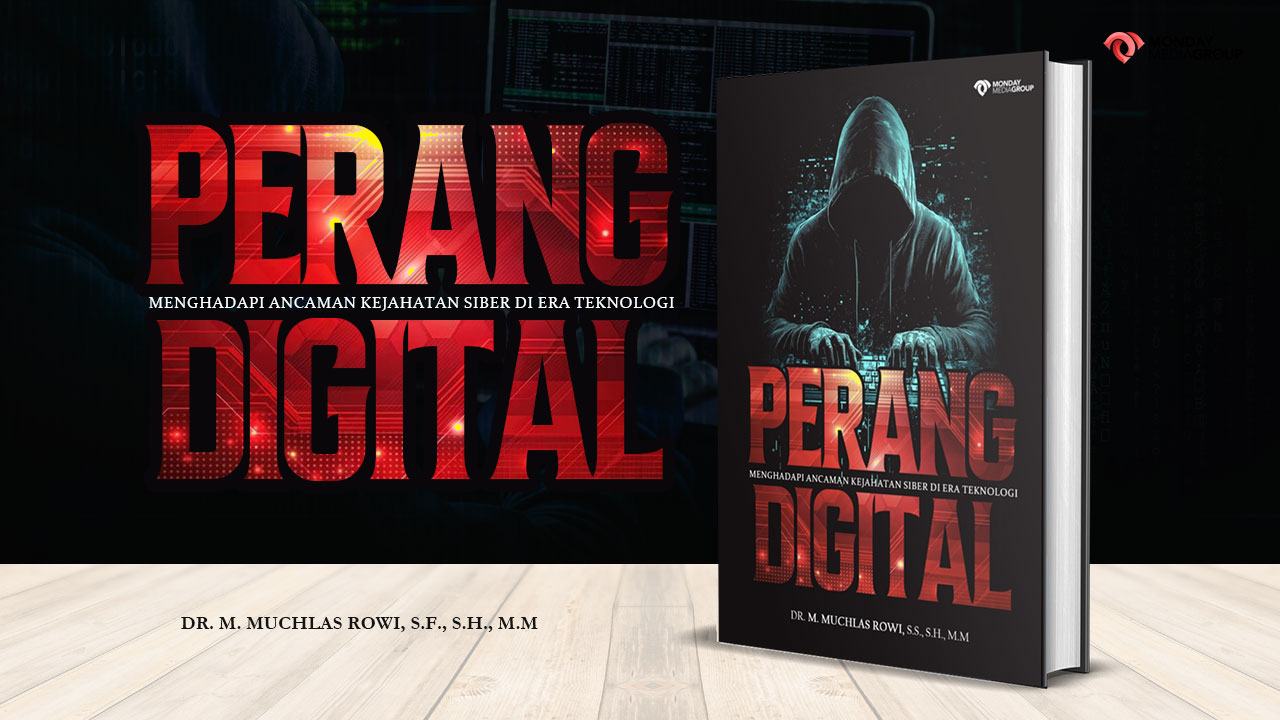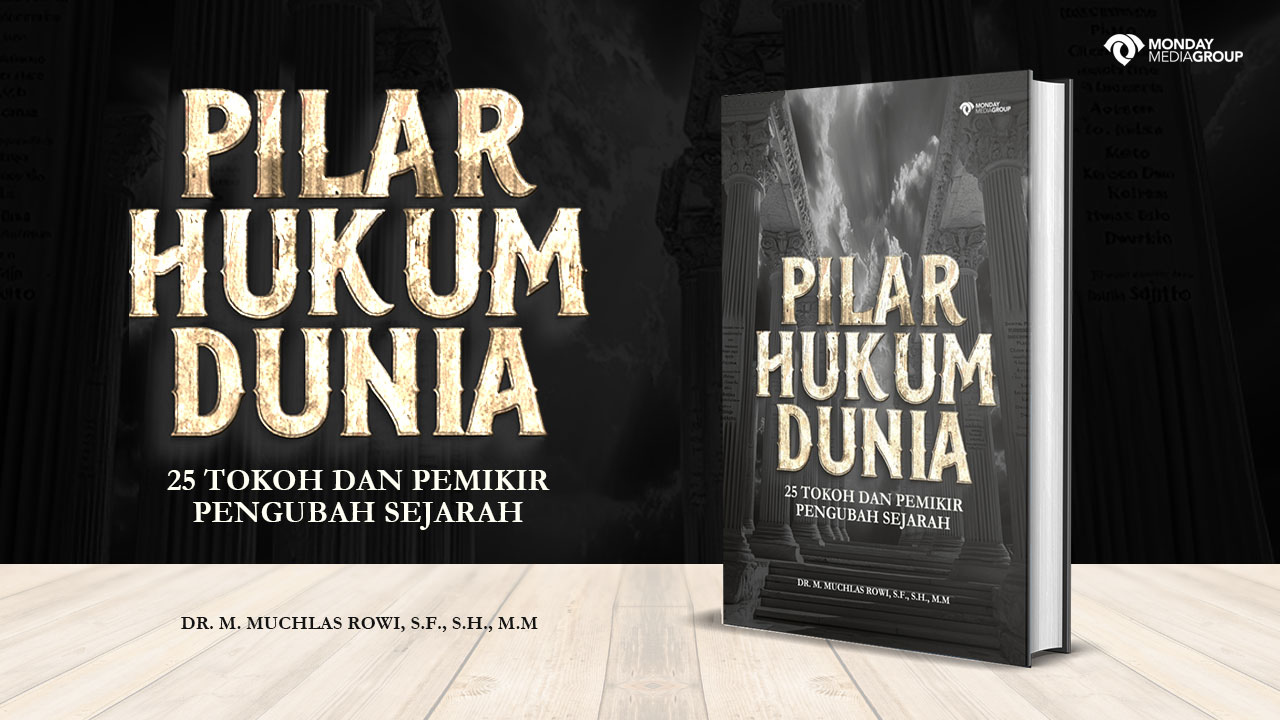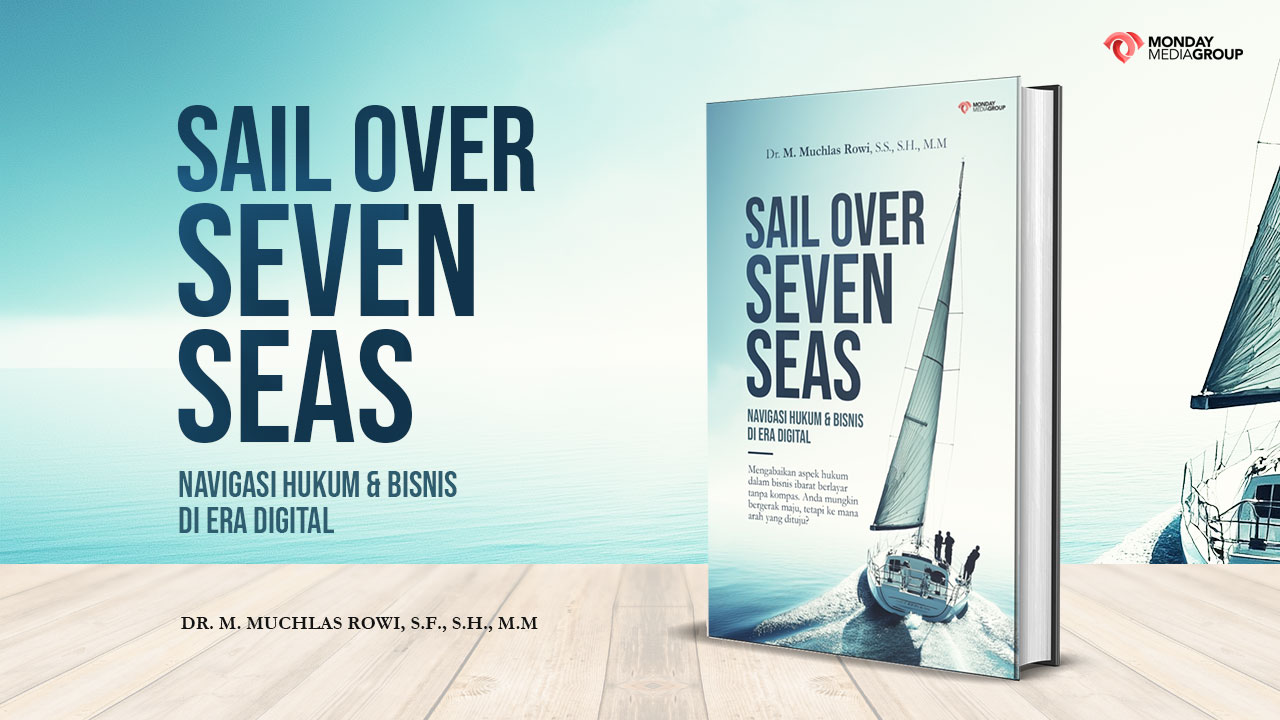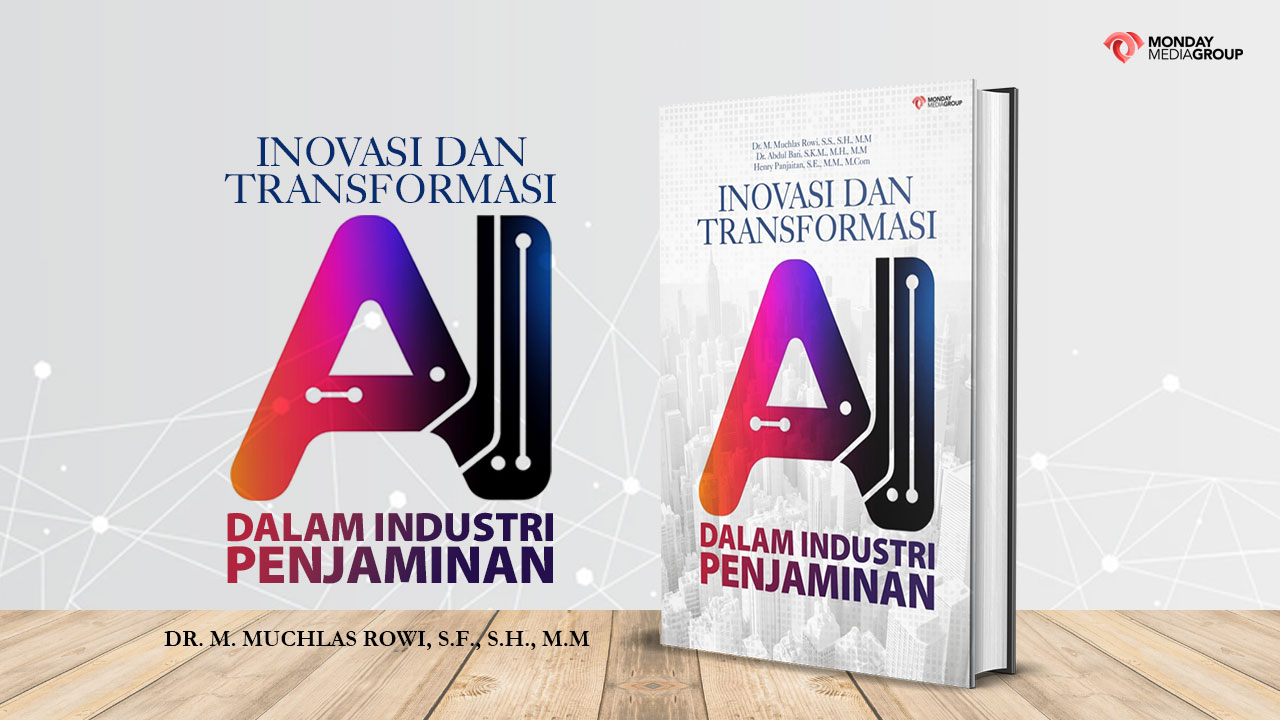Saat saya menulis buku Perang Digital, satu hal yang terus membayang di benak saya adalah betapa kita semua—tanpa terkecuali—sudah menjadi “warga dunia maya” yang aktif. Kita kirim pesan lewat WhatsApp, menyimpan file penting di cloud, belanja lewat e-commerce, bahkan curhat di media sosial. Dunia digital memberi kita kenyamanan dan kecepatan. Tapi, di balik layar itu, ada perang yang tak kasatmata sedang terjadi.
Perang ini bukan soal tank dan rudal, tapi soal data, sistem, dan celah keamanan. Lawannya pun bukan negara, tapi penjahat siber yang bisa bekerja dari mana saja, tak terlihat, dan nyaris tak tersentuh. Itulah kenapa saya merasa penting untuk menulis buku ini—bukan sebagai pengingat akan bahaya, tapi sebagai panduan agar kita semua lebih waspada.
Kita hidup di era yang disebut oleh Robert Mueller, mantan Direktur FBI, sebagai masa di mana “hanya ada dua jenis perusahaan: mereka yang sudah diretas dan mereka yang belum tahu kalau mereka sudah diretas.” Kalimat itu terdengar ekstrem, tapi sayangnya… benar adanya.
Buku ini bukan semata kumpulan teori atau istilah teknis yang bikin dahi berkerut. Saya justru ingin membawakan isu keamanan digital secara apa adanya—berangkat dari kasus nyata, data terkini, dan fenomena yang mungkin sudah kita alami, tapi tak kita sadari. Seperti ketika password kita tiba-tiba tak berlaku, atau ketika akun kita mengirim pesan aneh ke teman-teman.
Saya memulai dengan mengenalkan bagaimana teknologi seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, dan AI telah merevolusi hidup kita. Tapi, semua itu ibarat pisau bermata dua. IoT menghubungkan segala hal, mulai dari kulkas sampai CCTV, tapi banyak di antaranya tak punya sistem keamanan yang layak. AI bisa mendeteksi pola serangan lebih cepat, tapi juga bisa digunakan untuk menciptakan serangan phishing yang lebih meyakinkan, bahkan suara palsu (deepfake) dari atasan kita.
Salah satu bagian penting yang saya bahas adalah bagaimana kejahatan siber sudah menjadi industri. Ada yang disebut Ransomware-as-a-Service—ya, betul, semacam “franchise” kejahatan siber di mana siapa saja bisa menyewa layanan untuk menyerang orang lain. Bahkan, orang yang tak bisa koding pun kini bisa jadi penjahat siber berkat platform gelap seperti itu.
UKM, yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi, justru jadi target paling empuk. Banyak dari mereka berpikir, “Ah, usaha saya kecil, siapa yang mau repot-repot nge-hack?” Justru karena mereka kecil dan keamanannya lemah, pelaku lebih senang menyerang mereka. Lebih gampang, cepat dapat hasil, dan korban cenderung membayar karena tak siap.
Saya juga menggali kasus-kasus besar, seperti kebocoran data oleh peretas bernama Bjorka di Indonesia. Bagaimana data jutaan orang, termasuk data pejabat dan lembaga negara, bocor dan diperjualbelikan. Efeknya bukan hanya reputasi pemerintah yang tercoreng, tapi juga kepercayaan publik yang terkikis.
Dari sini, saya ingin menegaskan: serangan siber bukan hanya persoalan teknologi. Ini soal kepemimpinan, soal budaya organisasi, dan soal kesadaran kolektif. Kita sering kali tergoda menganggap “IT security” sebagai tugas bagian IT saja. Padahal, keamanan siber adalah tanggung jawab semua orang. Bahkan, banyak insiden justru dimulai dari kesalahan manusia—klik tautan mencurigakan, pakai password yang sama di semua akun, atau login di WiFi umum.
Dalam salah satu bab, saya menulis, “Ancaman siber bukan hanya soal sistem yang dibobol, tapi juga soal kepercayaan yang dirusak.” Kalimat ini lahir dari observasi bahwa setelah serangan terjadi, yang paling sulit pulih bukan data atau uang, tapi rasa aman pengguna.
Lalu, apakah kita tak bisa menang dalam perang digital ini? Bisa. Dan itulah pesan optimis dari buku ini. Ada banyak langkah nyata yang bisa kita lakukan: dari membangun budaya keamanan, melatih karyawan, hingga mengadopsi prinsip zero-trust. Teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, dan pemantauan aktivitas anomali juga kini semakin canggih dan terjangkau.
Tapi semua itu akan sia-sia tanpa satu hal: kesadaran. Kesadaran bahwa dunia digital bukan ruang kosong. Ia penuh celah, penuh pengintai, dan penuh risiko. Tapi, seperti kata pepatah: kapal tak akan karam hanya karena air di luar, tapi karena air yang masuk ke dalam. Kita harus menjaga agar air itu tak masuk.
Akhir kata, buku ini saya tulis bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, saya ingin membekali pembaca agar lebih siap, lebih tenang, dan lebih strategis dalam menghadapi era yang semakin digital. Karena dalam dunia yang makin terkoneksi ini, keamanan bukanlah pilihan—melainkan kebutuhan.