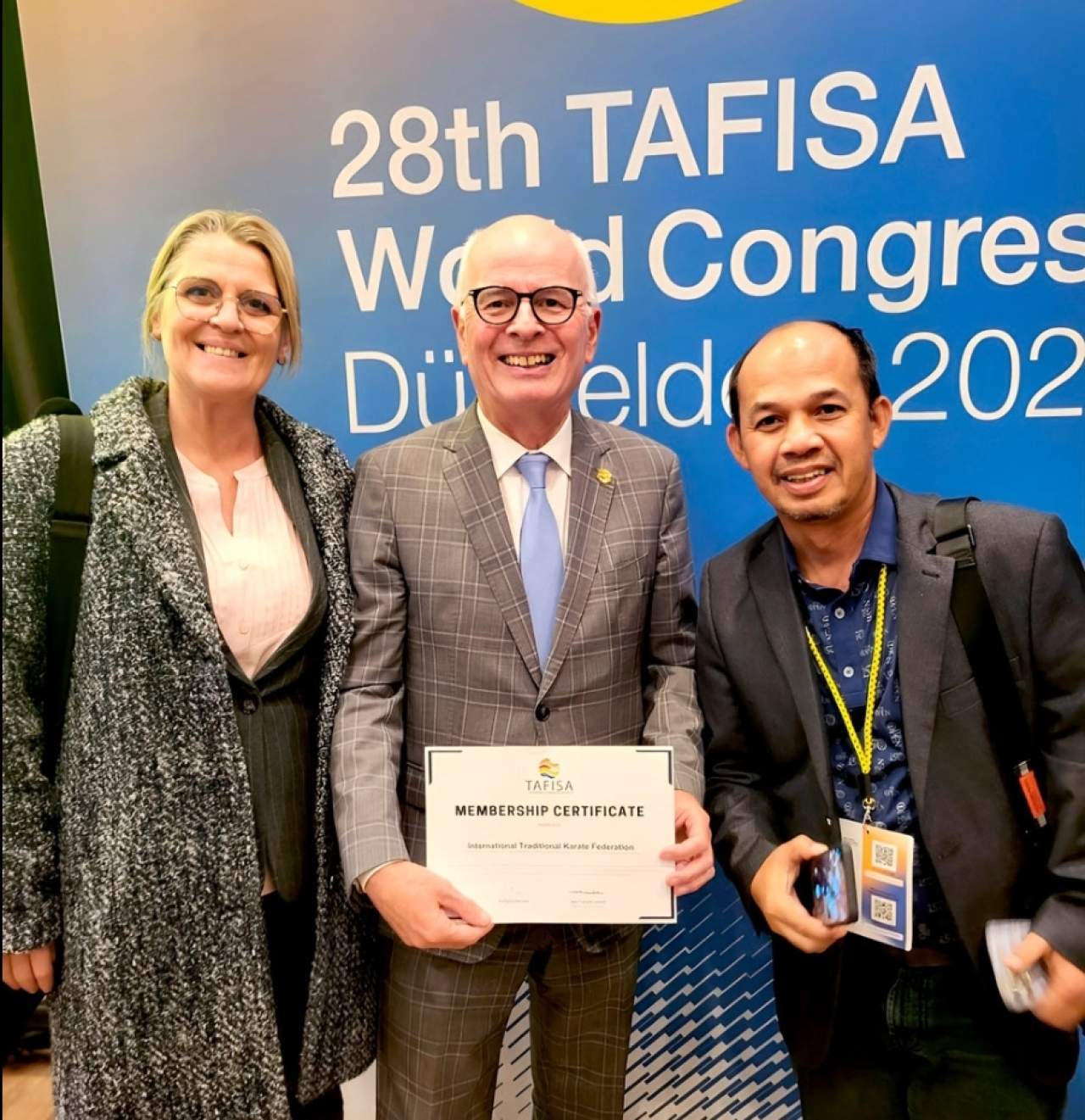RASANYA baru kemarin kita bersorak sorai atas keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Curacao kali kedua. Permainan anak asuhan Shin Tae-yong pun dipuja puji, karena berhasil menyajikan permainan apik dan mengalahkan Tim yang dihuni beberapa pemain EPL itu.
Sesaat, membuat kita bangga dan membusungkan dada. Lalu merasa layak membombardir akun instagram pemain Curacau yang katanya bermain di Birmingham City, Juninho Bacuna.
Namun, kebanggaan itu pun langsung hilang, seiring terjadinya tragedi kemanusiaan pasca laga Arema Malang versus Perbaya di Stadion Kanjuruhan. Ibarat ‘menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri’, tragedi Kanjuruhan membuat kita disorot dan dikecam publik sepakbola dunia.
Tragedi Kemanusiaan
Syahdan, laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur sejatinya nyaris mulus tanpa rusuh. Lantaran laga itu hanya disaksikan Aremania. Sementara para Bonek Mania memutuskan untuk absen di Kanjuruhan.
Namun, skor akhir 2-3 rupanya membuat suporter tuan rumah kecewa. Ungkapan kekesalan, hingga lemapran kecil ke arah lapangan lalu dimulai dan memancing Aremania merangsek masuk ke lapangan. Mereka menyerbu pemain baik dari Persebaya maupun tim Arema FC. Situasi makin memanas dan tanpa kendali setelah suporter melemparkan botol air mineral, batu, kayu.
Petugas yang melihat situasi tak bisa dikendalikan pun mulai menembakkan gas air mata. Akibatnya, suporter pun berlari tak terkendali. Berebut cepat keluar stadion, menghindari gas air mata yang membuat mata perih dan nafas kian sesak.
Malam itu, fanatisme pun berubah jadi kerusuhan maut. Hampir 125 orang kehilangan nyawa, sementara ratusan orang lainnya luka-luka.
Ternyata, tak perlu lama menunggu lahirnya kembali seorang diktator atau bangkitnya PKI agar kita bisa melihat tragedi kemanusiaan di negeri ini. Karena tragedi itu, dengan mudah mampu dibuat kembali oleh fanatisme, baik agama, ideologi, atau bahkan olahraga seperti terjadi di Kanjuruhan, Malang.
Padahal, banyak orang percaya sepakbola merupakan alat pemersatu bangsa, dia mampu mengalahkan apa pun termasuk konflik dan kediktatoran. Seperti dilakukan Legenda Chelsea Didier Droghba saat menghentikan pertikaian di negerinya. Atau Bintang Bayern Munchen, Sadio Mane yang sukses mengubah desanya yang miskin, jadi sebuah kota yang bergeliat.
Revolusi Sepakbola Indonesia
Sifat kompetitif sepakbola sejatinya telah membuatnya punya peran penting dalam catatan sejarah. Dimana bangsa-bangsa saling bersaing dan para individu berjuang menjadi yang terbaik. Sepakbola lantas bisa mengubah jalannya sejarah.
Rabu Legi, 29 Mei 1985, peristiwa serupa di Kanjuruhan pernah pula terjadi di Stadion Heysel, Brussels, Belgia. Saat Final Liga Champions yang mempertemukan Liverpool dan Juventus. Sekira 39 orang tewas dan 600 orang luka-luka akibat ulah para suporter yang naik pitam gara-gara saling ejek.
Sebuah dinding pembatas tiba-tiba runtuh, akibat tak kuat menahan suporter The Reds yang memaksa merangsek ke tribun para suporter Juventus.
Peristiwa kelam yang kemudian dikenal dengan Tragedi Heysel ini lantas membuat Liverpool terkan sanksi sangat berat. Bukan cuma denda ratusan juta atau permintaan maaf pejabat terkaitnya, melainkan larangan bermain 5 tahun di seluruh kompetisi Eropa.
Gara-gara tragedi ini, Liga Inggris pun melakukan revolusi kompetisi. Mengubah parameter keamanan, melakukan pendataan dan menerapkan aturan super ketat soal penonton.
Aturan baru paling gila adalah menghilangkan pagar pembatas tribun penonton dan lapangan serta tidak lagi menjual tiket tanpa kursi. Mereka sempat dikecam karena aturan ini. Bagaimana tidak, ada pagar saja rusuh, bagaimana jika tanpa pagar? Namun akhirnya semua orang memberi acuangan jempol.
Aturan ketat, dan hilangnya pagar pembatas ternyata membuat suporter di Liga Inggris dewasa.
Belajar Pada Bulu Tangkis
Meski sama-sama pernah mengalami peristiwa kelam dalam sepakbolanya, Inggris tentu saja berbeda dengan Indonesia. Di Negeri Ratu Elizabet, sepakbola adalah olahraga paling populer dan punya sejarah panjang.
Berbeda dengan di Indonesia, dimana sepakbola menjadi nomor dua terpopuler setelah bulu tangkis. Paling tidak hal ini seperti survei yang dilakukan Nielsen Sports, yang mencatat bulu tangkis sebagai olahraga terpopuler di Indonesia.
Survei yang dirilis Nielsen sports ini dirilis tahun 2020, dan menyebut 71 persen penduduk indonesia menyukai bulu tangkis. Sementara 68 persen menyebut suka sepakbola.
Artinya, perubahan sepakbola di Indonesia tak sekadar membutuhkan perubahan sistem, namun juga kultur.
Pejuang revolusi Kuba, Che Guevara pernah mengakui jika ia banyak dibantu sepakbola saat berjuang mewujudkan Revolusi Kuba. Sepakbola kata dia, memudahkan dirinya saat menjangkau rakyat. Ada kedekatan yang bisa ia bangun tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama dengan bola di kakinya.
Meski begitu, Che juga mengakui sejumlah tantangan yang dia temui saat mengusung revolusi Kuba sekaligus revolusi sepakbolanya. Karena sepakbola bukan olahraga populer di sana. Seperti halnya Castro, rakyat Kuba lebih menyukai Bisbol ketimbang sepakbola.
Lalu, bagaimana membuat revolusi sepakbola sekaligus revolusi Kuba bisa tercapai. Menurutnya, sepakbola itu harus menjadi milik masyarakat.
Seperti juga kuba yang mati-matian menggeser popularitas bisbol menjadi sepakbola. Indonesia pun mestinya begitu, harus mampu menggeser atau paling tidak membuatnya setara dengan bulu tangkis.
Tentu saja tak cuma soal prestasi, tapi juga tradisi. Di sepakbola, kita belum menemukan orang-orang seperti Keo Sophal. Yang rela melewatkan kesempatan meraih karir profesional, dan pulang ke desanya untuk memajukan sepakbola di negerinya, Kamboja.
Berbeda dengan tradisi di bulu tangkis, dimana kita bisa melihat ada orang-orang atau bahkan institusi yang rela membuat pusat-pusat pelatihan untuk edukasi atau bahkan sekadar hobi.
Pada akhirnya, revolusi sepakbola Indonesia memang harga mati. Selain agar para suporter tak selalu kecewa dan bisa membusungkan dada. Revolusi sepakbola juga jadi ukuran, seberapa dewasa kita.